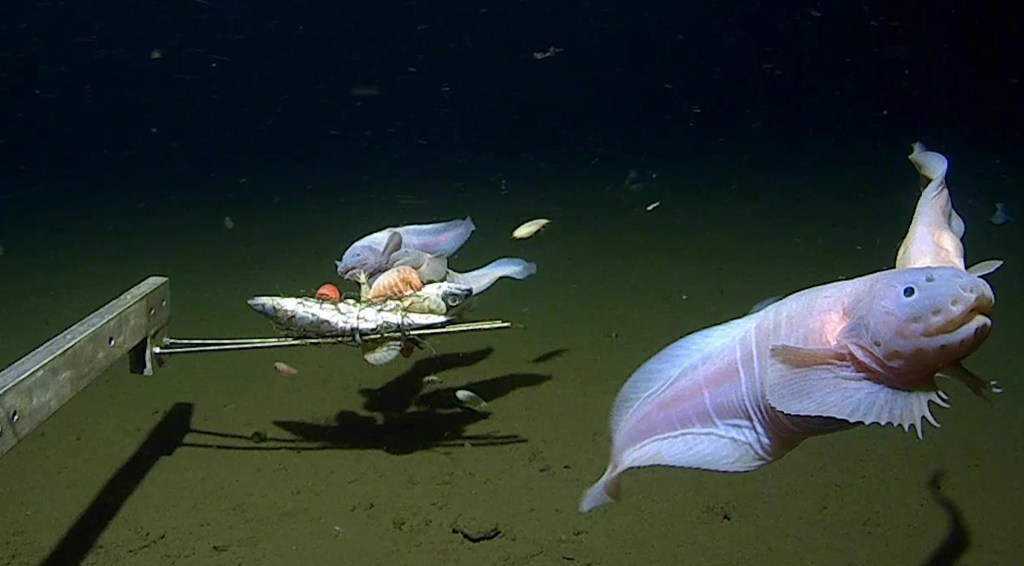Tiga hal terlintas di kepala kala mendengar nama Muara Angke: sampah, banjir, reklamasi. Awalnya prasangka saya itu seakan menemukan buktinya. Begitu mendekati pelabuhan, bau amis ikan bercampur bau comberan segera menusuk indera penciuman. Sampah menumpuk dan menyumbat aliran got di sepanjang jalan. Beberapa warga mengakui, saat memasuki musim penghujan dan pasang laut, banjir setinggi betis sudah pasti tak terelakkan.
Padahal, sebelum menjadi seperti sekarang, Muara Angke merupakan wilayah penting bagi nusantara. Lima abad lalu Muara Angke adalah urat nadi penting aktivitas penduduk Sunda Kelapa. Wilayah ini menjadi saksi pertempuran Kesultanan Banten melawan kapal perang Portugis pada awal Abad 16. Muara Angke juga turut menjadi salah satu pusat perdagangan Pulau Jawa sekaligus menjadi saksi bisu budaya asing yang berjalin kelindan dengan kearifan lokal. Namun persoalan menjadi semakin pelik satu dekade terakhir. Derap pembangunan dan masifnya roda-roda industri melupakan sepenuhnya jasa Muara Angke bagi peradaban bangsa ini.
Videos by VICE
Kini Muara Angke didera banyak masalah. Kawasan hutan bakaunya punah. Nyaris tak ada komoditas di perairan sekitar Muara Angke. Pencemaran logam berat ditambah rencana proyek reklamasi membuat nelayan di pesisir Jakarta terpaksa melaut lebih jauh lagi—bahkan hingga perairan Lampung. Banjir rob tahunan terus memaksa penduduk untuk mengungsi. Hingga isu penggusuran permukiman nelayan tradisional yang terus membayangi.
Terakhir saya ke Muara Angke adalah ketika membuat laporan soal kisruh reklamasi awal tahun ini. Wajah Muara Angke tak banyak berubah, mungkin hanya menua dan lelah. Air lautnya masih tetap berwarna hitam tertutup sampah. Deretan kapal-kapal nelayan besar dan kecil terus menggempur dermaganya.
Siang itu, saya memutuskan berjalan menyusuri jalanan pelabuhan menyambangi tempat pelelangan ikan (TPI). Saya termasuk penggemar masakan berbahan ikan laut. Di Jakarta, banyak kawan bilang tempat terbaik buat membeli ikan segar nyaris terbatas, selain Muara Angke.
Dari pintu gerbang, saya berjalan lurus sekira 200 meter sebelum berbelok ke kiri ke arah TPI. Dermaga tersebut terlihat sepi, hanya ada beberapa motor lalu lalang. Deretan truk terparkir di gudang-gudang penyimpanan ikan di kiri-kanan jalan. Beberapa nelayan tampak bermalas-malasan dengan bersembunyi di kolong kontainer, menghindari teriknya matahari yang tak seperti hari-hari biasanya.
Pemandangan yang sama tampak di TPI. Sepi. Apa mungkin saya terlambat karena kegiatan jual beli ikan cuma terjadi di pagi buta?
“Kalau mau beli ikan justru malam hari bang,” kata Aswin, salah seorang nelayan asal Indramayu yang sedang nongkrong di dermaga saat saya tanya. “Kalau siang kan pada melaut.”
Saya menyesali kebodohan ini. “Goblok banget kok enggak googling dulu sih!”

TPI Muara Angke adalah salah satu pasar ikan tersibuk di Jawa, mengundang nelayan—tradisional maupun modern—dari berbagai daerah untuk mengais rupiah. Setiap hari sekitar 500 ton ikan masuk ke TPI ini, jelas Aswin. Hasilnya: duit miliaran rupiah berputar di TPI ini saban harinya.
“Ada 400-an pedagang di TPI ini. Kalau pedagang besar bisa menjual puluhan ton,” tutur Aswin. Gondok karena enggak bisa belanja ikan, saya memutuskan berjalan menyusuri dermaga. Mata saya tertuju pada deretan warung semi permanen, menjajakan olahan ikan segar tangkapan.
Saya agak ragu buat jajan makanan di sini. Kandungan merkuri biota laut Teluk Jakarta sudah mencapai 40mg/kg dari ambang batas aman yang seharusnya 1mg/kg. Bayangan cerita tragedi Teluk Minamata di Jepang bergumul di kepala. “Gimana kalau nanti mules atau salah-salah kena penyakit serius?” batin saya berontak.
Namun saya tetap memutuskan mampir ke salah satu warung. Hanya ada sedikit pengunjung yang makan di situ. Biasanya para pengunjung adalah turis yang hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu atau warga Jakarta yang sengaja mencari ikan segar (seperti saya).
“Ikan-ikannya enggak ditangkap di sini kok mas,” kata Parti si pemilik warung, seakan bisa menebak kecemasan di pikiran saya. “Kan pada nangkepnya jauh-jauh. Di sini mana ada ikan.”

Saya memilih ikan yang dipamerkan di meja depan. Ada cakalang, kue, baronang, ikan ayam dan cumi. Saya memilih cakalang dan kue. Dengan cekatan Parti melumuri ikan dengan bumbu dan meletakkannya ke pembakaran. Tak sampai 30 menit, dua ikan tersaji di depan mata. Perut yang sedari pagi belum diisi ditambah dengan semilir angin laut membuat selera makan membuncah. Dalam hitungan menit, dua ikan tandas menyisakan tulang.
Ada semacam sensasi tersendiri yang tak bisa dijelaskan ketika makan ikan bakar di pinggir laut, meski bumbu yang digunakan tergolong sederhana: bawang putih, kecap, bawang merah, garam. Jelas berbeda dengan suasana makan di restoran.
Tampaknya judul tulisan ini tak berlebihan. Hanya butuh waktu kurang dari satu jam sambil menikmati ikan bakar untuk menyadari bahwa Muara Angke adalah salah satu warisan budaya penting. Di situ saya juga menyadari bahwa alam masih berbaik hati memberikan hasil lautnya.

Jika suatu hari nanti pulau-pulau reklamasi telah dipenuhi gedung dan apartemen yang menjulang, apakah deretan warung ikan bakar tradisional tersebut bakal berganti menjadi restoran yang megah nan angkuh, dengan tembok tebal yang menghalangi embusan angin laut? Saya tak kuasa membayangkan.
Seandainya para pejabat dan bos-bos properti itu menghabiskan waktu satu jam dengan makan ikan bakar dan melihat sekeliling, apakah keadaan di Muara Angke akan berubah menjadi lebih baik? Saya harap begitu.
Jadi, cobalah satu kali saja menuju Muara Angke. Nikmati sajian ikan bakar di sana. Lain kali, ketika ada pejabat atau orang yang ngotot memaksakan reklamasi, ingatkan soal pasar ikan dan warung-warung sederhana di sana. Itu adalah harta karun yang sebaiknya tak dikorbankan atas nama pembangunan.