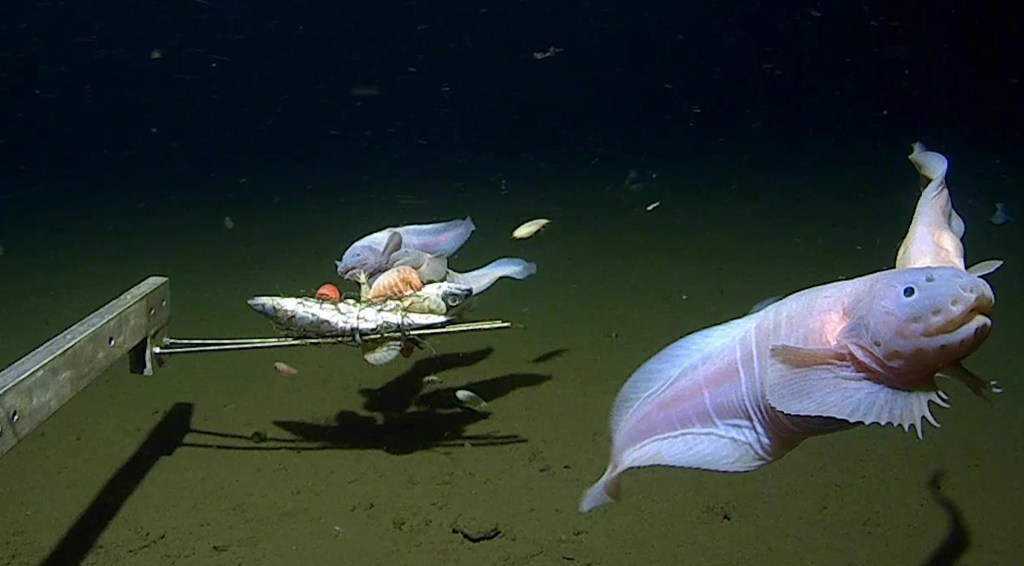Juli 1979, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah kampung pesisir pulau Seram, Maluku Tengah. Ia kelak dikenal dengan sapaan Pak Moh. Seorang nelayan pemancing tuna yang ulet. Rumahnya di sisi teluk tempatnya menambatkan perahu, dan berhadapan langsung dengan kaki gunung Binaya, juga dikenal dengan sebutan Gunung Nunusaku.
Nunusaku adalah gunung agung yang dijaga penduduk Kepulauan Maluku. Sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat pertama kali manusia turun ke Bumi lalu berpencar menghuni pulau-pulau kecil di Maluku.
Videos by VICE
Pak Moh rutin memandangi gunung itu antara pukul 03.00 hingga 04.00 dinihari, ketika dia mulai berjalan pelan ke perahu, lalu menaikkan semua perbekalannya. Ada tasi sebagai tali pancing, batu untuk pemberat, umpan cumi, cairan hitam cumi, dan makanan.
Saat penglihatan masih samar-samar, ratusan pemancing tuna membelah selat itu menuju arah laut Banda. Raungan mesin dengan kekuatan 15 PK membentuk busa di belakang perahu. Semua bergerak dalam harapan yang besar.
Pak Moh punya nama lengkap Muhammad Silawane, mewarisi marga dari wilayah bernama Tehore itu. “Saya ingat, sejak kecil saya sudah ke laut bersama bapak. Ikut memancing,” katanya.
Pak Moh seperti kebanyakan warga di kampung Tehoru, tak bisa lepas dari laut. Orang tuanya ingin dia bersekolah dan melanjutkan pendidikan agar bekerja di darat. Tapi sekolah membuatnya bosan, sementara laut selalu memanggil-manggilnya, terutama untuk menangkap tuna. Di Tehoru, nelayan pancing khusus tuna mencapai 500-an orang.
Dekade 1980-an akhir, dia ingat betul, nelayan di kampungnya hanya menggunakan perahu kecil dengan layar. Mereka mendayung ke tengah teluk dan mulai membuang mata pancing. Cakalang dan tuna masih mudah dijumpai dan didapatkan. Orang-orang di pesisir yang membutuhkan ikan hanya tinggal mengasoh di bawah naungan pohon, lalu menunggu nelayan dan membeli hasil tangkapan.
Tapi semakin tahun, peruntungan memburuk. Ikan cakalang dan tuna mulai enggan masuk ke perairan. Nelayan generasi selanjutnya seperti Pak Moh terpaksa merogoh kocek lebih dalam atau mengajukan kredit ke bank untuk memperoleh pendanaan pembuatan perahu. “Tak ada pilihan, saya sendiri mengambil kredit di bank untuk perahu. Menabung bagi nelayan agak sulit, karena setiap hari harus melaut,” ujarnya.

Di depan tambatan perahunya, kami duduk bersantai di atas pasir kerikil pantai yang hangat. Meneguk kopi dan meluruskan kaki. Tiba-tiba di kejauhan di lautan yang tenang itu, ada beberapa sirip ikan berbentuk segitiga yang nampak. Leher Pak Moh menegang, pandangannya mengawasi gerakan itu. “Lumba-lumba?” tanya saya.
“Iya, tapi itu bukan lumba-lumba yang baik. Itu Gajah Mina,” sahut Pak Moh.
Gajah Mina di wilayah seperti Bali, Flores dan beberapa kepulauan Maluku dianggap sebagai hewan mitologi. Wujudnya kerap dijumpai di beberapa Makara, atau patung dalam kepercayaan Hindu. Di Sumatera pada era kedatuan Sriwijaya, Makara Gajah Mina ini perwujudannya ditampilkan dengan badan berbentuk ikan dan memiliki belalai seperti gajah, yang dianggap sebagai penguasa lautan.
Berbeda dengan Tehoru. Nelayan setempat meyakini Gajah Mina bukanlah binatang mitologi, melainkan jenis mamalia laut. Dalam buku seri indetifikasi hewan laut yang diterbitkan Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI) para nelayan menemukan gambar Gajah Mina itu. Nama latinnya Grampus griseus atau Risso’s dolphin.
Risso’s dolphin memiliki panjang maksimum 3,8 meter. Sirip punggung yang tinggi dan melengkung seperti sabit. Sementara kepala membulat, dan tak memiliki paruh. Lumba-lumba ini juga diketahui sebagai satu-satunya dari genus Grampus yang dekat kekerabatannya dengan Paus Pilot serta Paus Pembunuh.
Bagi nelayan di Tehoru, Risso atau Gajah Mina dianggap sebagai ikan “pencuri”. Hidup berombongan dan selalu mendekati nelayan untuk mengambil hasil pancingan. “Kalau pancing sudah dapat tuna, atau ikan lain. Gajah Mina itu selalu duluan mengambilnya,” kata Pak Moh.
“Jadi kalau ikan sudah kena pancing, itu kan tidak bisa banyak bergerak karena ada tasi. Ikan tidak bebas berenang. Nah itu Gajah Mina itu akan lebih cepat ambil,”
“Kita juga mau turun ke laut, bahaya. Bisa juga digigit.”
Bagi nelayan, bertemu Gajah Mina di lautan berarti pertanda sulit mendapatkan ikan. Gajah Mina yang hidup dalam kawanan dan menyebar untuk memburu, juga membuat ikan menghindar. Pada 27 November 2022, inilah yang dirasakan puluhan nelayan pancing tuna di Tehoru. Mereka yang mulai melaut pada dini hari, harus pulang ke daratan menjelang siang dengan tangan hampa. “Mau bagaimana lagi. Mau usir atau mau bunuh juga tidak selesaikan masalah. Jadi pulang istirahat,” kata La Tohia nelayan lainnya.
La Tohia lahir tahun 1981. Dia menjadi pemancing tuna sejak usia SMP. Nelayan tua di Tehoru mengajarkannya, jika Gajah Mina juga memerlukan hidup. Nelayan tak boleh menganggunya, sebab sama seperti manusia, mamalia laut itu mencari makanan. “Ya mungkin dua atau tiga hari, Gajah Mina akan berpindah cari tempat makan lagi. Ikan itu tidak selamanya di sana,” katanya.
Bagi La Tohiah, kunci menjadi nelayan adalah menjadi sabar. “Kalau suasana hati sedang tidak bagus, banyak masalah. Rezeki di lautan juga seperti itu. Jadi nelayan itu harus ke laut dengan senang karena untuk bekerja,” tandasnya.
Keberlanjutan Jadi Kunci Bertahan di Tehoru
Menjauhnya ikan membuat wilayah pencarian ikut terpengaruh. Rata-rata setiap nelayan pemancing tuna, dalam sekali jalan dari dinihari hingga jelang pukul 17.00 menghabiskan antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu menjangkau jarak sekitar 10 mil.
Biaya terbesar membeli bahan bakar jenis pertamax, di mana harga setiap liternya kini dipatok Rp14.200 untuk kawasan Maluku. Perahu mesin 15 PK sekali trip menghabiskan sekitar 40 liter. Nelayan Tehoru sudah kerap mengeluhkan kelangkaan bahan bakar yang lebih terjangkau dari Pertamax, tapi tak ada jalan keluar dari otoritas yang berwenang.
Terlepas dari persoalan bahan bakar, sebetulnya cara memancing nelayan tuna di Tehoru merupakan praktik ramah lingkungan yang layak dipuji. Pancing ulur mereka tidak menggunakan banyak mata kail, apalagi pukat harimau yang merusak ekosistem. Mereka memakai satu bentangan tasi satu kail, dengan cumi-cumi sebagai umpan.

Para nelayan melilit potongan umpan cumi itu disebuah batu seukuran kepalan tangan orang dewasa. Di ujung lilitan yang menempel di batu, nelayan membuat simpul lepas, lalu batu itu ditenggelamkan ke perairan. Kedalamannya bisa mencapai 30 meter.
Ketika nelayan sudah memperkirakan kedalaman yang dibutuhkan, dari atas kapal, nelayan menghentak tali pancing agar lilitan di batu terlepas. Setelah itu, nelayan tak memegang pancingnya untuk merasakan gigitan ikan, melainkan membuang kotak gabus yang menjadi ujung tasi ke lautan. Dalam sekali trip, setiap nelayan, rata-rata membawa sekitar 30 sampai 50 batu sebagai pemberat umpan.
Bagi nelayan, praktik pancing dengan tidak banyak berpindah dan menggunakan batu sebagai pemberat ini dilakukan ketika bahan bakar mulai mahal. Sebelumnya, praktik yang dilakukan adalah memancing dengan memperhatikan gerakan lumba-lumba, nelayan akan mengejar rombongan mamalia laut di belakang dan membuang kail. “Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan, karena kehabisan bahan bakar di tengah lautan,” kata La Tohia.
Praktik lainnya adalah menggunakan layang-layang. Umpan tali pancing akan diikatkan di layang-layang dan nelayan akan menerbangkannya di tengah lautan. Sayang praktik ini juga menguras bahan bakar.
Bagaimanapun, ikhtiar nelayan tuna untuk tetap ramah lingkungan membuahkan hasil. Tuna tangkapan nelayan di Tehoru, yang sekian tahun terakhir turut didampingi MDPI, mendapatkan logo Fair Trade, dan telah didistribusikan di sekitar 1.200 toko di Amerika Serikat. Ini sertifikasi yang sulit diraih kebanyakan nelayan Asia Pasifik. Sebab, syarat memperolehnya adalah seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perdagangan tuna ini wajib berlangsung adil serta berkelanjutan. Khususnya bagi si nelayan dan komunitasnya.
Ini kabar menggembirakan, terlebih karena industri tuna secara global punya reputasi miring. Tuna terancam punah karena obsesi konsumen di berbagai negara. Proses penangkapan dan pengolahannya juga sangat buruk. Penelitian pada 2018 menunjukkan di Asia Tenggara, mayoritas nelayan dan produsen tuna melakukan praktik pemancingan ilegal, merusak rantai ekosistem, bahkan terindikasi melibatkan perbudakan manusia. Artinya, capaian di Tehoru ini terhitung langka.
Sertifikasi itu cukup membanggakan nelayan Tehoru, meski dengan sedikit catatan. Para nelayan Tehoru tidak menjual ikan tuna dengan sistem gelondongan per ekor, tapi dengan memisahkan daging dengan bentuk fillet. Rata-rata nelayan mendapatkan tuna satu ekor sebesar 14 kilogram, yang jika dikemas fillet, menjadi sekitar 8 – 9 kilogram.
Setiap bulan, nelayan tuna akan melakukan trip antara 15 hingga 20 hari. Dan jika dikalkulasi keuntungan rata-rata nelayan setiap bulan, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta. “Tapi keuntungan itu tidak kelihatan langsung setiap bulan. Karena dalam satu waktu, bisa saja tidak dapat ikan. Atau hanya satu ekor. Jadi simpanan awal akan diambil kembali untuk membeli perbekalan,” kata Pak Moh.
“Jadi bayangkan kalau tiga kali trip tidak dapat apa-apa? Bisa tidur di perahu, tidak pulang ke rumah, karena simpanan juga sudah habis. Makanya ada nelayan yang terpaksa mengutang untuk modal,”
“Tapi menjadi nelayan masih tetap baik, jika harga stabil.”
Fadlan Silawane merasakan bagaimana menjadi nelayan masih menjajikan. “Dulu saya kerja di kantor, tidak bisa punya rumah hanya kontrak. Sekarang sudah bisa bangun rumah sendiri,” katanya.
Fadlan berusia jelang 40 tahun. Dia adik Pak Moh. Sebelumnya dia bekerja di kantor pajak di Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagai tenaga kontrak selama 16 tahun, dia mengaku tak bisa menanggung hidup istri dan tiga orang anaknya hanya dengan gaji kurang dari Rp4 juta kala itu.
Tahun 2018, dia memutuskan kembali ke kampung di Tehoru. Dia ikut belajar ke Pak Moh, bagaimana cara memancing tuna. “Di Kalimantan, kerajaannya banyak dalam ruangan dan berpendingin udara. Di laut bila hujan akan kena hujan, panas juga begitu,”
“Belum lagi badai. Kulit juga sudah sangat gelap karena terbakar. Tapi menjadi nelayan, jauh lebih bebas.”
Sayangnya tetap ada satu noktah hitam. Setiap nelayan di Tehoru meyakini usia dan produktivitas nelayan paling banter cuma sampai 55 tahun. Setelah itu energi dan kepiwaian melaut berkurang. “Ini yang berbeda dari petani. Petani menanam sekarang, akan bisa menikmati hasil tanamnya sampai dia tua dan bahkan tidak bisa bekerja lagi,” kata Fadlan.
“Kalau nelayan, kalau sudah tua istirahat tidak bisa lagi ke laut. Apa yang diwariskan ke anak? Ya keterampilan. Jka tak ada generasi yang menjadi nelayan, ya garis keluarga itu akan selesai dalam dunia nelayan.”
Cinta Pada Laut di Tehoru
Bagi nelayan, membicarakan laut adalah membicarakan halaman mereka bertumbuh dan mencari nafkah. Laut yang tenang dan bergejolak adalah bagian dari siklus yang tak bisa diubah. “Jadi kami nelayan hanya mempelajarinya. Kalau kenal laut, berarti kenal juga tempat bekerja,” kata Pak Moh.
Saya meminta beberapa nelayan berbicara mengenai petuah penting bekerja sebagai nelayan. Salah satu yang menggelitik: berhubungan seks dengan istri sebelum ke laut bisa meningkatkan keberuntungan saat mencari ikan.
Alasan mereka sederhana, istri yang ditinggalkan di rumah merasa senang dan suami yang ke laut juga bahagia. Di pesisir Tehoru, dari pagi hingga sore, saya menyaksikan anak-anak nelayan itu bermain. Apakah mereka generasi yang pembuahannya direncanakan pada dinihari sebelum orang tuanya melaut? Pak Moh, tertawa mendengar ungkapan itu.
Pada 28 November 2022, di pesisir Tehoru, seratusan anak desa dari usia Sekolah Dasar, SMA, hingga pemuda, menyisir pantai dan mengumpulkan sampah yang tak bisa terurai agar tak mengotori lautan. Mereka dengan antusias, memasukkannya dalam kantong sampah dan membawanya ke bank sampah desa.

Di saat bersamaan, beberapa anak berlarian mengejar layangan yang putus agar tidak jatuh ke laut. Seorang anak kemudian memperhatikan arah angin dan memilih tempat terbaik. Celananya basah, tapi dia berhasil menangkap layangan itu.
Di sisi pantai yang lain, di waktu yang sama, seorang lelaki menggendong anak perempuan yang bertelanjang. Dia turun dengan pelan dan membenamkan badannya di lautan. Anak perempuan itu memeluk si lelaki. Lalu tangan lelaki itu membasuhkan air laut itu ke kepala si anak. Dia membuka ikatan rambut, dan terus melakukannya. Seperti ritual.
“Di Tehoru kami lakukan banyak hal di laut. Anak-anak bermain, orang tua bermain. Laut juga adalah obat untuk beberapa penyakit,” kata Pak Moh.
Tak heran, Pak Moh kemudian dengan sukarela bergabung dalam kegiatan bersih pantai itu. Dia menunjuk tumpukan popok bayi dan beberapa sampah plastik. “Kalau pantai kotor, bagaimana anak-anak bermain. Kalau kotor, kalau mandi, pasti akan sakit, pasti gatal,” katanya.
Sampah akibat ulah manusia, kata La Tohia, mungkin alasan beberapa ikan tak masuk lagi ke teluk. “Pesisir masih kelihatan bersih. Tapi coba berenang ke sana, di bawah dasar itu, segala rupa sampah sudah ada,” katanya menunjuk lautan.
Laporan ini turut didukung oleh Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Eko Rusdianto adalah jurnalis lepas yang bermukim di Makassar. Liputannya yang lain untuk VICE bisa dibaca lewat tautan berikut.